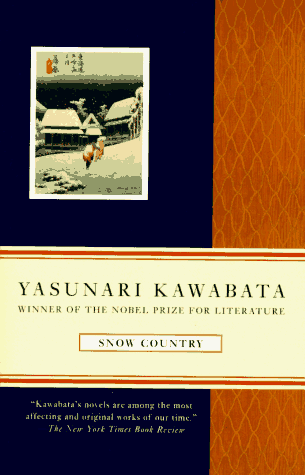--Arif Saifudin Yudistira--
Apa yang dirasakan
oleh seorang tapol,keadaan jiwanya, kesedihan, keterasingan dan jiwa yang hampa
bagi seorang tapol?,semua itu dilukiskan dengan baik oleh Rudolf Mrazek(2000)
dalam bukunya Pramoedya Ananta Toer dan
Kenangan Buru. Buku ini adalah cara Rudolf Mrazek menyusun sebuah memori
dan perasaan-perasaan Pramoedya yang dikaitkan dengan kehidupan yang ada di
sekitar Pram. Pram sebagai seorang korban, tahanan politik mengalami dengan
langsung, apa yang dimaksud dengan kebohongan, manipulasi, dan segala perlakuan
yang tak adil. Pram pun sadar, bahasa-bahasa politik dibentuk melalui ruang
tahanan, perenggutan kebebasan, dan hak-haknya direnggut dan dirampas. Betapa
ia menderita dan mengalami kekacauan pikiran (amnesia) karena pernah dipoprol
senapan kepalanya waktu mau ditangkap dan dibawa ke Buru. Hal ini terlihat
tatkala Pram ditanya : “Darimana anda mendapatkan kertas untuk menulis?”, ia
justru menjawab : “aku mempunyai delapan ekor ayam”.Tidak hanya itu, tetapi di
dalam tahanan itu, Pram memiliki banyak teman yang mengurusnya tatkala ia
sakit, dan dari teman-teman itulah ia tak lagi merasakan kesepian, lebih dari
itu, Pram juga memiliki jaringan jenderal yang secara tak langsung ikut
membantu Pram. Dikisahkan tatkala Pram mau dibawa ke Jakarta setelah
kepulangannya dari Buru, ia pun mengenali jenderal disana, sehingga ia dibawa
pulang ke rumahnya, Blora. Walaupun pada akhirnya ia akan memilih hidup ke
Jakarta kelak. Pramoedya, dengan segala sifat-sifat manusiawinya, pada akhirnya
ia menyadari bahwa kekagumannya terhadap barat, ia pun menuliskan kekaguman ini
dengan mengatakan : “Belanda memungkinkanku melihat kecantikan sebuah
masyarakat yang terorganisir, bagaimana jasa setiap orang dihargai berdasarkan prestasinya,
dan bagaimana setiap orang memiliki hak memperoleh sarana untuk tetap hidup…Aku
tidak bisa lagi menjadi penulis kacangan” (h.21).Pram, pada saat dia di Buru
justru menemukan waktu dalam tiga dimensi sebagaimana yang ditulis Rudolf
Mrazek. Pram sebagai seorang yang di tahanan mengingat-ingat apa yang telah ia
alami, ia pun kemudian menyusun kenangannya sendiri. Kenang-kenangan sewaktu ia
memiliki cita-cita menjadi insinyur. Ia menyukai radio, sehingga ia masuk ke
Sekolah Teknik Radio. Pramoedya harus menyusun ulang tak hanya hidupnya,
kenang-kenangannya, sampai pada dokumentasi dan apa saja yang pernah ia
kumpulkan. Tak hanya perkara mesin ketik, tetapi melalui mesin ketik itu pula,
ia menyusun kembali ingatannya, kenang-kenangan dan hidupnya. Ia pun berencana
menyusun roman tentang periode kebangktia nasional (h.96).
Buru seperti tabung
inkubasi, ruang pengeraman, Pram justru menelurkan karya-karya dan suaranya,
yang tak hanya berurusan dengan pribadinya, melainkan juga untuk kebesaran
bangsanya sebagaimana kata Mayor Kusno waktu memberi hadiah pulpen dan kertas
di Pulau Buru. Pram menyadari bahwa bangsa yang tak mengenali sejarah kebesaran
bangsanya, ia tak mampu diharapkan membawa bangsa ini kepada arah yang benar.
Sebagaimana yang sering disesalkan Pramoedya selama ini, bahwa kita sudah
terlampau melenceng dari kebudayaan asali kita, budaya maritime. “bagaimana
mungkin bangsa yang sebesar Majapahit dan Sriwijaya justru memperbesar angkatan
darat, memperkuat angkatan darat?”. Apa yang ditulis Pram membuka kesadaran dan
mata batin kita kembali, bahwa perjuangan, nasionalisme, pahit getir dan
keterasingan yang dialami pejuang di masa itu adalah demi kemerdekaan.
Kebebasan, demi cita-cita luhur bangsa kita, yakni kemerdekaan yang bebas dari
kolonialisme dan penjajahan. Pram pun demikian halnya, meski ia mengalami
penyiksaan dan pengasingan, Pram mampu membuktikan bahwa ia masih bisa
bersuara, menulis dan mengabarkan yang benar dari kejahatan rejim.
Rudolf Mrazek
menuliskan Pram dan Kenangan Buru ini sebagai dokumentasi bahwa apa yang
dialami Pram identik dengan Syahir, meski keduanya mengalami pengasingan,
Rudolf Mrazek mencoba membangun narasi dari seorang tokoh yang seolah sedang
memberi kesaksian sejarah, kesaksian bagi sebuah bangsa yang merdeka, sebuah
bangsa yang pernah mengalami masa kelam. Melalui buku ini, kita diajak untuk
merenungi kisah para tahanan, para tapol yang mengalami penyiksaan jiwa.
Sehingga bekas dari siksa itu, tak bisa lekas sembuh, bahkan sulit untuk
sembuh. Penyiksaan itu melampaui urusan fisik semata, lebih dari itu, ia
dipisahkan dari anak-anaknya, keluarganya. Bahkan Pram pun menyurati anaknya,
karena khawatir surat-suratnya tak sampai. “Surat
Untuk Nen”/Ayah tidak menerima sepucukpun suratmu selama dua tahun terakhir.
Barangkali surat-suratmu tidak disampaikan padaku/atau apakah kau benar-benar
menulis surat pada waktu itu?.Surat Pram ini tidak hanya dibaca sebagai
kesedihan Pram atas tekanan yang dialami jiwanya. Ia juga merupakan ekspresi
kekecewaan dari sebuah pengasingan dan ketidakadilan yang dialaminya. Melalui
buku ini, kita belajar tentang makna pengasingan, kesepian dan kesendirian
sebagai seorang tapol, kenangan dan catatan itu kelak berguna untuk kita
sebagai bangsa sebagai rekam jejak kejahatan dan kebrutalan rezim yang
melanggengkan kekuasaan dengan genoside seperti bangsa kita. Mrazek, tak hanya
mencoba mengajak kita kembali kepada masa lalu, masa sekarang dan masa yang
akan datang. Pelajaran yang bisa diambil dari Pramoedya Ananta Toer tak lain
adalah pengasingan bukanlah proses untuk tenggelam dan mati, ia akhirnya
menunjukkan bahwa perjuangan dan pengasingan akan membawa kepada masa depan
yang lebih tegar,kuat dan menenteramkan meski harus ditempuh dengan kepahitan
yang tak bisa dilupakan.
*) Penulis adalah Santri Tadarus BUKU BILIK
LITERASI SOLO