Kesepian, lebih tepatnya “hening” yang digambarkan oleh Kawabata, membawa kita memasuki dunia batin manusia dengan ceruk yang dalam, yang tak bisa dengan mudah digambarkan oleh seorang penulis lain selain ia sendiri
Yamako,
melebihi apa yang saya tahu selama ini tentang Geisha, Geisha adalah bagian
dari kesadaran cultural, saya termasuk asing menemui kisah Geisha. Saya merasa
tertolong dengan Kawabata, ia mengisahkan Geisha sebagai seorang malaikat yang
tak bisa disepelekan begitu saja. Kehadirannya tak hanya urusan hiburan dan
seksualitas semata. Kawabata menghadirkan emosi, menghadirkan sejarah, biografi
dan riwayat keluarga dengan segala lika-likunya. Saya jadi ingat apa yang
dikatakan Komako saat ia bilang : “Aku
orang yang paling susah, dan tuan belum pernah merasakan apa yang saya rasakan”.
Kalimat pendek itu adalah penggalan perasaan dari Komako, Geisha yang memenuhi
lakunya dengan : kerja! Kerja! Kerja!. Kisah Komako akhirnya harus diselesaikan
dengan indah, saat ia mengalami perpisahan justru dengan keluarganya sendiri.
Yoko dalam hal ini adalah bagian dari keluarga Geisha, meski ia tak menjadi
Geisha. Dalam hidup Komako, Yoko memiliki makna penting, tak sekadar sebagai
teman, sebagai pelayan dan juga rekan kerja meski berbeda pekerjaan. Shimamura
pun demikian, seorang tua yang sudah punya isteri, sudah beranak, pada akhirnya
harus memilih tempat untuk meredakan kembali hari dan hatinya yang sedang
gundah. Di saat-saat itulah, ia melakukan pengabaian kepada Komako meski ia
menaruh cinta padanya. Ia justru menaruh gairah, ketertarikan pada Yoko. Yang
menarik dari novel Kawabata ini, adalah bagaimana ia mengisahkan kehidupan,
kesepian, seorang yang sudah berumur, sudah berkeluarga, yang ingin menemukan
kembali apa yang telah hilang dari hidupnya.
Apa yang dihadirkan
oleh Kawabata mengajak saya merenungkan kembali sajak yang ditulis oleh Rendra,
Bersatulah Pelacur Jakarta. Sajak itu seolah mengembalikan dan
membalikkan pengertian kita selama ini tentang pelacur. Ia melampaui cerita dan
kisah serta dogma-dogma agama yang cenderung menganggap pelacur sebelah mata.
Ia manusia, ia hidup seperti kita, dan ia pun berhak memiliki emosionalitas
seperti kita, dan tak jarang ia merasakan putus asa dan lemah dengan
ketidakberdayaannya. Simaklah betapa Komako mampu menghadirkan pertanyaan yang
tajam kepada Shimamura. “Manusia itu rapuh,kan?” kata Komako pagi itu. “Hancur
jadi bubur dari kepala hingga ke tulang-tulang. Tapi seekor beruang bisa jatuh
dari tempat yang tinggi dan tidak terluka sama sekali”. Kalimat-kalimat ini
adalah tamparan bagi Shimamura, pun bagi Komako sendiri. Shimamura, lelaki ini
pun adalah lelaki tua takberdaya, rapuh, dan begitu ringkih, hingga ia
memerlukan tempat, memerlukan perempuan untuk mengembalikan dirinya seperti
sediakala. Begitupun Komako, ia begitu jatuh, dan merasa menjalani hidup dengan
tertatih-tatih, meskipun ia merasa sudah
menemukan cintanya, Komako perlu waktu untuk bisa berdiri tegak dan
tegap berjalan dengan tenang.Kesepian, lebih tepatnya “hening” yang
digambarkan oleh Kawabata, membawa kita memasuki dunia batin manusia dengan
ceruk yang dalam, yang tak bisa dengan mudah digambarkan oleh seorang penulis lain selain ia sendiri.
Kawabata mampu untuk mengisahkannya pada kita tentang dunia pelacur, dunia
buku, dan kisah manusiawi di sekitarnya. Bila Komako menghabiskan novel dan cerpen
yang cukup dalam, dan menuliskannya dengan indah, maka kita seperti di tampar
oleh cermin besar, disana ada perempuan, disana ada riwayat dan kehidupan yang
sering diremehkan. Komako, seolah mengingatkan kepada kita, dalam dunia dan
kebudayaan Jepang, pelacur adalah manusia yang sadar akan posisi, kebudayaan,
sastra, yang tak boleh diperlakukan sebagai penghibur semata. Ia adalah sosok
perempuan yang mengaduk-aduk perasaan, emosi dan juga menelanjangi kehidupan
para tetamunya, sebagaimana yang dialami oleh Shimamura dalam novel ini. Saya
jadi teringat dengan apa yang dituturkan Pramoedya mengenai gundik, Pram
mengangkat Ontosoroh sebagai seorang perempuan Jawa dengan segala kelebihan dan
kehebatannya, ia tak sekadar gundik semata, ia adalah wujud perlawanan yang
meskipun pada akhirnya harus kalah.
Kartasura, 4/ 9/14
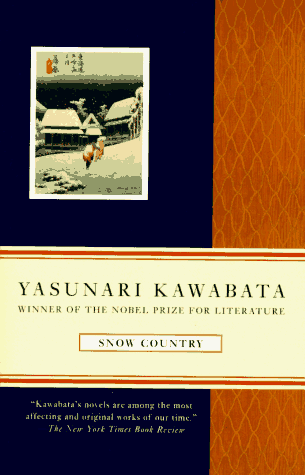
No comments:
Post a Comment